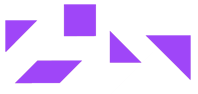Sweet Seventeen: 17 Tahun Eksperimentasi MES 56
Oleh Alexander Supartono

Tahun 2017 lalu, DECK Photography mengundang MES 56 untuk berpameran di ruang mereka yang dibangun dari tumpukan peti kemas di pusat kota Singapore. DECK adalah salah satu organisasi fotografi paling aktif dan populer di Asia Tenggara. Mereka menyelenggarakan Singapore International Photography Festival (SIPF) setiap dua tahun sejak 2008, pameran rutin dan program residensi. Pameran MES 56 adalah pameran inagurasi “Crossing SEA,” serial pameran untuk melihat perkembangan mutakhir fotografi di Asia Tenggara. DECK melihat MES 56 sebagai salah satu kolektif fotografi yang paling sukses dan berumur panjang di Asia Tenggara. Karenanya, pameran itu melihat bagaimana MES 56 sebagai kolektif mempengaruhi perkembangan fotografi kontemporer di Indonesia dan Asia Tengara. Dengan kata lain, A History of Boys, the MES 56 and Beyond: A Survey of Contemporary Photography in Indonesia adalah pengakuan dan perayaan atas keberhasilan kolektif dari Yogyakarta ini.
Menyambung pengakuan dari negri jiran di atas, tahun ini Galeri R.J. Katamsi, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, mengundang MES 56 berpameran di institusi dimana sebagian besar (kalau tidak semua) pendiri kolektif ini belajar pada awal dan pertengahan 1990-an. Undangan ini adalah undangan untuk pulang, atau lebih tepatnya undangan untuk mengunjungi rumah dimana mereka pernah tinggal. Tentu saja ada unsur nostalgia di situ, namun yang lebih penting, undangan pameran itu menawarkan kesempatan refleksi diri bagi para eksponen MES 56 dan terutama bagi ISI Yogyakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan fotografi formal tertua di Indonesia. Bagi generasi awal MES 56, mengunjungi titik awal perjalanan fotografis mereka ini adalah sebuah restrospektif: melihat secara kritis perkembangan artistis dan tematis praktek fotografi mereka hampir 25 tahun terakhir, baik secara individu maupun kolektif. Bagi departemen fotografi ISI, pameran ini dapat menjadi lensa refleksi untuk memeriksa seberapa jauh keterlibatan mereka dalam perkembangan fotografi kontemporer di Yogyakarta dan Indonesia dalam dua dekade terakhir.
Namun perkara pengakuan bukan soal baru bagi MES 56. Kehadiran mereka di dunia seni kontemporer tidak pernah sepi sambutan. Belum juga genap setahun, salah satu gelaran seni rupa terbesar dan tertua di Indonesia, Biennale Jogja mengundang mereka berpartisipasi di edisinya yang ke-7 tahun 2003. Walau MES 56 resmi mewujud tahun 2002, para anggota pendirinya sudah aktif kerja bersama sejak pertengahan 1990-an. Sejak dari bangku kuliah, mereka sudah mulai mereka-reka praktek fotografi dalam konteks seni rupa kontemporer yang mengatasi dikotomi antara keindahan fotografi salon dan tradisi fotografi dokumenter. Menjawab undangan Bienal Jogja di atas, MES 56 membangun studio foto komersial “gadungan” di dalam ruang pamer yang siap melayani pengunjung bienal. Foto-foto studio para pengunjung itu kemudian dipajang dan dijual. Praktek fotografi interaktif ini mereka beri judul “Keren dan Beken” dan menandai karya kolektif pertama MES 56. “Keren dan Beken” mengingatkan kita pada konsep seni relasional (relational aesthetic) dari teoritisi seni Perancis Nicolas Bourriaud, yang melihat pentingnya hubungan sosial sebagai landasan operasional praktek artistik dan kemampuan karya seni untuk membangun lingkup-lingkup sosial yang khas (specific sociability). Interaksi pengunjung Biennale (foto bersama, foto mereka bagian dari pameran, membeli foto) adalah rangkaian aktivitas sosial yang membangun lingkup sosial khas yang terbentuk dan difasilitasi oleh studio foto “Keren dan Beken.” Interaksi sosial ini jauh lebih penting daripada praktek fotografinya sendiri. Dengan demikian, lewat praktek fotografi populer, “Keren dan Beken” memaparkan hubungan sosial di dunia seni rupa kontemporer Yogyakarta dimana interaksi sosial, jaringan pekerja seni dan perkawanan menjadi sumber inspirasi dan berperan vital dalam produksi artistik.

Lebih jauh lagi, “Keren dan Beken” juga menggambarkan karakter representasi diri dalam potret studio. Karena itu, proyek kolektif pertama MES 56 ini bisa diterjemahkan sebagai pandangan kolektif mereka terhadap status fotografi dalam dunia seni kontemporer Indonesia. Dengan membawa budaya populer (studio foto) ke panggung seni yang mapan seperti Bienal Jogja, MES 56 memperkenalkan banalitas praktek fotografi keseharian (vernacular photography) sebagai praktek seni tinggi (highbrow art). Dengan tidak berfokus pada “foto” tapi pada “praktek” fotografi yang menghasilkan interaksi personal dan sosial, “Keren dan Beken” memperluas nilai dan wilayah operasional dari medium ini. Lebih penting lagi, elemen sosial yang dimungkinkan oleh praktek fotografi inilah yang menjadi prosedur operasional MES 56 secara keseluruhan, tidak hanya dalam produksi karya kolektif, tapi dukungan kolektif terhadap produksi karya individual anggotanya. Di tengah atmosfir kolektif ini, anggota MES 56 mendapatkan dorongan artistik, dukungan teknik dan tentu saja kritik dalam diskusi-diskusi intensif yang mungkin karena ruang kerja, studio dan tempat tinggal yang berbaur jadi satu. Rekanan dekat MES 56 dan kritikus seni yang disegani Antariksa dengan jitu merangkum dinamika kolektif ini: “… karya yang keluar meskipun dibrandoli nama-nama individu, itu sebenarnya hasil intervensi bersama.”

Lingkup kolektif ini lalu meluas ketika MES 56 mulai membuka program residensi dan mengundang seniman, kurator, peneliti dan penulis lokal, nasional dan internasional untuk bekerja, memproduksi dan mempresentasikan hasilnya di ruang mereka. Program ini menjadi ajang pertukaran gagasan dan praktek fotografi seturut (dan mematangkan) kecenderungan artistik yang berkembang di MES 56. Setelah 17 tahun berjalan, dimana produksi karya (kolektif atau individual), pameran, diskusi, dan presentasi terus berkesinambungan, kecenderungan-kecenderungan itu terformulasikan menjadi karakter fotografis (estetis dan teknis) yang khas MES 56. Bahkan bisa dibilang, karakter itu menjadi identitas kolektif MES 56. Karakter inilah yang kemudian diterima sebagai salah satu bentuk praktek fotografi kontemporer di Indonesia dan Asia Tenggara.
Kemeriahan pasar seni rupa kontemporer Indonesia di pertengahan 2000-an kadang dilihat sebagai faktor penting yang mendukung umur panjang MES 56. Walau tak bisa dipungkiri bahwa kemeriahan pasar seni rupa dan acara-acara seni besar telah menyediakan ruang artistik dan operasional yang lebih leluasa, sekaligus dukungan finansial tidak langsung, tapi perlu diingat pasar itu bereaksi terhadap praktek fotografi MES 56 dan bukan sebaliknya. Dengan kata lain, eksplorasi dan eksperimentasi mereka dengan fotografi, ditambah kejelian mengidentifikasi tema dan gaya yang sedang populer, menjawab, kalau bukan menciptakan, kebutuhan ‘fotografi seni’ di pasar seni kontemporer Indonesia. Walau fotografer Indonesia sudah berpartispasi di acara seni rupa besar sejak Bienal Seni Rupa Kontemporer Jakarta 1993–1994, bisa dibilang justru perupalah yang membawa fotografi ke dalam praktek seni rupa kontemporer Indonesia, seperti bisa kita lihat pada karya foto etsa dari FX Harsono yang berjudul “Republik Indochaos” (1998) karya instalasi Agus Suwage berjudul “Pink Swing” (2005, kolaborasi dengan fotografer Davy Linggar). Fotografer harus bekerja di profesi yang lebih jamak seperti jurnalis foto ataupun fotografer komersial. Dari kerja-kerja “non-seni” inilah mereka mensubsidi partisipasi mereka dalam pameran-pameran seni rupa (bahkan pameran fotografi sekalipun). Proyek-proyek fotografi non-jurnalistik dan non-komersial jumlahnya juga terlalu sedikit untuk mendukung kelangsung praktek fotografi seni. Pendiri MES 56 Angki Purbandono dan Wimo Ambala Bayang, kemudian disusul Agan Harahap adalah generasi awal fotografer Indonesia yang bisa 100% fokus pada kerja-kerja artistik mereka. Dalam konteks ini, keberhasilan MES 56 adalah membawa kembali praktek dan wacana “fotografi seni’ dari tangan perupa ke tangan fotografer.
Pameran We Go Where We Now di galeri Katamasi, ISI Yogyakarta ini adalah pameran retrospektif karya-karya kolektif MES 56. Selain memajang karya-karya kolektif, mereka juga menyertakan dokumentasi dan arsip di seputar karya-karya tersebut agar pengunjung dapat menelusuri proses kreatif dari setiap karya. Lebih jauh lagi, mereka memindahkan ruang MES 56 (dengan segala aktifitas rutin mereka) ke galeri selama pameran berlangsung. Dengan demikian pengunjung tidak hanya belajar bagaimana salah satu kolektif fotografi tertua dan paling aktif di Asia Tenggara ini membangun karakter estetis dan tematisnya, mereka juga bisa mengalami dan berpartisipasi para proses kreatif MES 56.Interaksi semacam inilah yang selama ini menjadi tulang punggung estetis MES 56.

Di pameran retrospektif, We Go Where We Now ini MES 56 menyertakan semua karya kolektif sejak “Keren dan Beken” dari tahun 2003 sampai yang terakhir “Alhammdulillah We Made It” dari tahun 2015.Seperti saya singgung di atas, “Keren dan Beken” direkontruksi di pameran Hisotory Boys di Singapore. Di edisi 2017, karya ini memaksimalkan potensi interaktif fotografi di era sosial media di dunia maya. “Keren dan Beken” di era facebook, twitter and instagram ini menggarisbawahi elemen ke-instan-an imaji/citra foto yang menjadi lingua franca interaksi sosial kita sehari-hari. Rekonstruksi ini mempertanyakan tidak hanya soal relevansi studio foto di era selfie dan wefie tapi juga menggugat ide romantis tentang figur fotografer yang selalu bekerja dalam kesendirian dan fungsi kamera sebagai medium yang canggih untuk menghadapi (dari pada mengalami) dunia. Penekanan pada unsur ke-amatiran-an dalam fotografi ini, digabung dengan strategi bermain dengan ironi (dari pada mengolah potensi naratif fotografi), menjadi wacana dominan di MES 56. Mereka menggunakan kamera tidak untuk menkonstruksi imaji fotografis yang canggih, tapi sebagai medium berbagi gagasan dan pengalaman. Pokok ini sangat fundamental dalam praktek artistik MES 56.

Mereka menggali lagi gagasan fotografi sebagai medium yang demokratis, terjangkau dan bisa digunakan oleh siapa saja, sebagaimana dibayangkan para penemu kamera dulu. Konsekuensinya, bagi mereka foto adalah bahan (bukan hasil akhir) untuk proses kreatif selanjutnya, sebagaimana kita lihat pada proyek kolektif mereka yang kedua “Holiday” (2004). Dengan metode cut and paste, mereka memidahkan figur-figur dari sebuah foto ke foto tempat liburan yang tidak pernah mereka kunjungi. Foto olahan ini lalu menjadi “bukti” bahwa mereka pergi berlibur. Praktek manipulasi foto semacam ini dipraktekkan sejak tahun 1840-an dan sekarang menjadi kegiatan jamak para digital native. Namun “Holiday” juga menyertakan foto ‘asli’ yang berlubang dan dipresentasikan diptychdengan hasil foto olahan. Dengan demikian “Holiday” tidak hanya mempertanyakan otoritas sebuah foto sebagai dokumen (bukti atas terjadinya sebuah persitiwa) tapi lebih dari itu, karya ini mengajak kitaberpikir lebih mendalam tentang fotografi dalam hubungannya dengan ‘kehadiran’ dan ‘ketakhadiran’ (presence and absence). “Holiday” mengajak kita melihat apa yang tidak terlihat dari sebuah foto, salah satu hal mendasar yang sering kita lupakan karena keterpesonaan kita pada kualitas pictorial dari sebuah foto. Dari sudut pandang ini, pendekatan fotografi keseharian pada “Holiday” menjadi pilihan yang logis. MES 56 memakai strategi serupa ini dalam karya kolektif mereka yang paling mutakhir, “Alhamdullillah We Made It” (2015). Dalam karya ini, mereka meng-copy paste foto-foto para pengungsi yang terdampar di Indonesia di lokasi yang menjadi impian mereka. Kalau foto sering dipakai untuk membangun nostalgia tentang masa lalu, di proyek ini MES 56 membalik logika itu dengan menjadikan fotografi sebagai medium untuk mewujudkan mimpi di masa depan.

Karya kolektif MES 56 selanjutnya “Unfolded City” (2005) bergerak di kitaran fungsi fotografi sebagai alat pengingat (mnemonic) dimana foto-foto tua (kolonial) Yogyakarta, yang sudah mereka bubuhi simbol-simbol kekinian, diproduksi sebagai kartu pos. Dalam karya ini MES 56, sekali lagi mempertanyakan otoritas fotografi sebagai dokumen sejarah. Namun lebih lagi, intervensi elemen-elemen ‘non-historis’ di dalam foto-foto historis itu, mengajak kita berpikir tentang relevansi sejarah pada keseharian kita. Dengan kata lain, mereka bertanya: “Apa fungsi foto-foto lama?” Jawaban mereka: “kartu pos!” Jawaban ini tidak hanya mengembalikan fotografi pada praktek keseharian (berkirim kartu pos), tapi juga fungsi fotografi dalam membentuk ingatan kita, tentang fotografi dan nostalgia. Dengan demikian di proyek ini, MES 56 memposisikan diri sebagai ‘tukang arsip’ yang menjadikan arsip sebagai sesuatu yang hidup dan relevan.
Kebalikan dari “Unfolded City”, pada “2nd Pose” (2008) MES 56 berperan sebagai produser arsip lewat serial potret seniman-seniman Jogja dengan latar belakang sudut-sudut kota yang mereka tinggali. Di sini, mereka bekerja seturut konvensi-konvensi visual fotografi yang lebih tradisional: komposisi, pembingkaian, pencahayaan, pemilihan tempat, penciptaan kontras dan drama. Jalur visual ini dipilih karena mereka ingin menggarisbawahi status seniman sebagai sebuah kategori sosial dan/atau profesi, yang untuk waktu yang lama secara administratif tidak diterima. MES 56 juga merespon elemen fotografi dalam administrasi sipil: foto (kartu) identitas yang monoton, tipologis dan tanpa ekspresi. Seturut logika ini, foto (kartu) identitas ini adalah “pose pertama” (the 1st pose) yang dilanjutkan oleh MES 56 ke “pose kedua” (the 2nd pose).

“Melawan Lupa” (2011) bisa disebut proyek refleksi diri MES 56 menjelang 10 tahun usia mereka, dimana mereka mengumpulkan kerja-kerja individual anggotanya dan dipresentasikan secara kolektif dalam bentuk buku foto. Fotografi di MES 56 secara umum adalah aktivitas digital. Sangat sedikit (kalaupun ada) anggota MES 56 yang bekerja dengan fotografi analog. Di era digital, fotografi analog menjadikan fotografi prakatek yang eksklusif, hal yang tentu saja bertentangan dengan haluan artistik MES 56. Dari perspektif ini, “Melawan Lupa” jadi proyek kolektif yang menarik karena di situ MES 56 mengakui keterbatasan fotografi digital, sambil mengingatkan kita (untuk melawan lupa), bahwa, sebuah foto adalah juga sebuah benda yang bisa disentuh, dipegang, dirasakan dan bukan hanya citraan (imagery) yang membutuhkan alat lain untuk melihatnya. Setelah cukup lama, MES 56 dalam proyek ini, bicara lagi soal aspek fisik dan material dari fotografi, bahwa foto itu bukan hanya kasat mata tapi juga kasat raga/benda.
“Mystical Mystery Tour” (2013) adalah satu-satunya karya kolektif MES 56 yang menggarap praktek artistik yang keluar dari dua dimesionalitas fotografi. Proyek ini bahkan tidak menyentuh aspek ‘pertunjukan’ (performativity) dari fotografi sebagaimana banyak dikerjakan seniman fotografi kontemporer. Sebenarnya hanya soal waktu MES 56 membuat proyek artistik tentang fenomena komersialisasi Jogja sebagai kota wisata. Masalahnya bukan hanya soal pemilihan topik yang jitu tanpa mengulang yang sudah-sudah, tapi juga soal pilihan pendekatan fotografisnya. Yang mereka pilih kemudian, kembali pada strategi artistik karya kolektif mereka pertama ”Keren dan Beken” tapi dengan meminimalkan aspek fotografinya ke melulu urusan dokumentasi dalam arti yang paling harafiah. Di proyek ini, MES 56 mengambil posisi sebagai pemandu wisata di Jogja yang menawarkan layanan kunjungan lokasi-lokasi magis di sekitar Yogyakarta. Kalau fotografi sering dilihat dan dipraktekan sebagai medium yang bisa menunjukkan elemen-elemen surealistik dalam kehidupan kita sehari-hari, di proyek ini, MES 56 justru memfasilitasi praktek-praktek surealistik itu. Artinya, mereka tidak lagi menggunakan fotografi untuk merepresentasikan elemen surealistik dari keseharian kita, tapi menggunakan diri mereka (yang adalah fotografer) untuk terlibat secara aktif dalam praktek itu. Pada saat yang sama, “Mystical Mystery Tour” menjadi parodi dari gagasan “seni terlibat” yang populer di kalangan seniman Yogyakarta di era 1980-an dan 1990-an. Proyek ini mereka ulang lagi tahun 2016, ketika MES 56 terlibat dalam gelaran konferensi internasional “Concept, Context, Contestation: Art and the Collective in Southeast Asia” yang diselengarakan di Yogyakarta. Dan ini kali, pengguna jasa mereka adalah para seniman, kurator, kritikus dan sejarawan seni internasional perserta konferensi itu. Luar biasa!

Sumbangan utama MES 56 pada wacana dan praktek artistik fotografi kontemporer adalah dengan memperluas ruang operasional fotografi ke wilayah seni rupa kontemporer. Mereka keluar dari wacana dan praktek tradisional fotografi dokumenter dan pada saat yang sama menghindari piktorialisme fotografi salon. Namun MES 56 mengambil antusiasme (dan keceriaan) dari fotografi hobbyist dan dengan cara mereka tetap berpegang pada misi tradisional fotografi dokumenter dimana kamera dipandang sebagai alat yang mampu berperan dalam perubahan sosial, lalu menggabungkan keduanya menjadi aktifitas artistik yang populer, interaktif dan mampu bicara masalah-masalah sosial aktual dari sudut pandang dan praktek fotografi keseharian.Penekanan mereka pada aspek amaturisasi (amateurisation) dari fotografi, dengan sikap yang rileks dan santai terhadap kamera sebagai teknologi perekam modern yang canggih dan karakter bermain dalam prosedur artistik mereka, menurut saya, adalah sumbangan terbesar MES 56 pada praktek fotografi kontemporer di Indonesia. Dengan sikap itu, mereka menciptakan kebebasan dan keleluasaan dalam bereksperimen dengan fotografi, mencoba kemungkinan yang tidak pernah (atau berani) dipikirkan kalau mereka tetap beroperasi di dalam pakem-pakem fotografi yang sudah baku. Pendekatan ini tidak hanya membawa kesegaran pada praktek fotografi kontemporer di Indonesia, yang untuk waktu yang lama terbeban oleh tanggung jawab naratif fotografi dokumenter atau keterlenaan fotografi salon. Tapi juga menawarkan praktek dan bentuk fotografi seni pada dunia seni rupa kontemporer Indonesia, tawaran yang tidak harus diacu pada praktek-praktek fotografi tradisional. Sebagaimana terbukti dalam 17 tahun terakhir, pendekatan mereka ini berhasil membuat fotografi tetap menarik dan inklusif, dan lebih penting lagi, akan terus memperpanjang umur MES 56.

Tulisan ini pertama kali diterbitkan di buku katalog pameran Ruang MES 56 “We Go Where We Now” di Galeri R.J. Katamsi ISI Yogyakarta, 28 Oktober-18 November 2019.