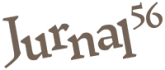Bagaimana Semestinya Seseorang Berhadapan dengan Kepasrahan?
— Sita Magfira

/1/
Perlu untuk mengaitkan proyek Fajar dengan status Yogya sebagai tujuan wisata. Status yang membuat pemerintah (dan mungkin juga sebagian dari kita?) sering berpikir kalau kota ini perlu kian “ditata”. Acapkali, “penataan” kota memberi dampak pada warganya. 12 tahun menetap di Yogya, tidak hanya sekali saya mendengar warga dipaksa pindah karena pembangunan akan dilakukan di ruang hidupnya. Ambil apa yang terjadi di Temon, Kulonprogo, dan Parangkusumo sebagai contohnya. Atau bagaimana warga yang tinggal di kawasan mepet njeron beteng bakal dipindah secara bertahap dalam waktu dekat, seiring dengan proyek revitalisasi beteng Keraton. Salah satu tahap awal dari proyek ini adalah rekonstruksi pojok beteng lor wetan (timur laut) demi mengembalikannya seperti sebelum peristiwa Geger Sepehi.
Rekonstruksi pojok beteng dilakukan dengan pertimbangan untuk melindungi dan menonjolkan potensi cagar budaya yang jadi aset pariwisata Yogyakarta. Ini mengingatkan pada pernyataan Kirshenblatt-Gimblett dalam “Theorizing Heritage” tentang turisme dan heritage sebagai dua industri yang kolaboratif. Lebih lanjut ia menjelaskan tentang bagaimana heritage menjadikan berbagai tempat sebagai tujuan wisata. Sementara turisme membuat tempat-tempat itu memiliki nilai ekonomi.
Rekonstruksi sendiri masih jadi topik bahasan dalam kajian heritage. Perlu tidaknya rekonstruksi untuk mencapai “keotentikan”, misalnya, adalah hal yang masih diperdebatkan. Dalam kasus-kasus hilangnya bangunan cagar budaya karena perang, rekonstruksi dipertanyakan lewat pandangan bahwa apa yang telah hilang, akan selamanya hilang dan tidak tergantikan. Mempertahankan reruntuhan bangunan yang hancur karena perang, seperti kasus pojok beteng lor wetan, cukup sering diajukan sebagai tawaran yang lebih baik daripada membangun sesuatu yang baru dari reruntuhan itu. Bukan saja karena reruntuhan bangunan lebih apa adanya, tapi juga karena ia bisa mengajarkan tentang perang dan dampaknya. Ditambah lagi, kelekatan antara industri pariwisata dan heritage membuat proyek-proyek rekonstruksi sering mendapat kritik karena dianggap dilakukan demi mengikuti tuntutan pariwisata dan modal ketimbang berdasar pemahaman historis.

/2/
Proyek Fajar memang tidak secara langsung menyinggung kompleksitas wisata dan heritage, tapi kisah-kisah yang direkamnya hadir dari kerumitan itu. Kawasan mepet njeron beteng lor wetan yang disinggung di atas adalah latar tempat dalam proyek Fajar kali ini. Fajar bertemu dan mendengarkan kisah-kisah sebagian warga yang akan segera “pindah” dari sana. Dari percakapan-percakapan awalnya dengan warga, Fajar menangkap kesan kalau mereka adalah orang-orang yang “sabar dan tawakal” atau penuh “kepasrahan.” Kesan itu membuat Fajar ingin tahu, “Apa sebenarnya harapan mereka atas situasi yang dihadapi?” Berhadapan dengan orang-orang yang “pasrah”, Fajar berpikir kalau menanyakan harapan adalah jalan yang tepat untuk mengenal mereka lebih dalam. Dengan mengajukan pertanyaan itu, Fajar seolah mengajak mereka untuk memeriksa kembali apa yang mereka rasakan dan pikirkan tentang perubahan yang hadapi. Temuan-temuan inilah yang kemudian dikumpulkannya dalam sebuah buku doa.
Ada momen-momen di mana Fajar khawatir kalau warga yang diajaknya berbincang akan tetap “pasrah” bahkan saat mengirim harapan dalam doa. Saya membayangkan kalimat macam, “Tuhan jika ini yang terbaik, berikanlah hambamu ketabahan untuk menghadapinya.” saat Fajar membagi kekhawatirannya itu. Mungkin waktu itu saya perlu bilang ke Fajar kalau orang-orang yang teraniaya punya kecenderungan untuk mengirimkan doa-doa yang lantang. Semangatnya bisa sama dengan memaki, hanya caranya saja yang berbeda. Terlepas apakah Tuhan atau kekuatan apapun di luar sana mendengarkannya atau tidak. Saya juga bisa membagikan bagian terfavorit di Embroideries karya Marjane Satrapi sebagai ilustrasi. Di sana, dengan komikal, Marjane menggambarkan seorang istri, yang bersuami seorang lalim, khusyuk mendoakan hal-hal buruk untuknya: “Tuhan, buatlah dia kena kanker.”, “Tuhan, biarlah dia ditabrak mobil.”, “Tuhan buatlah dia dibunuh perampok.”, “Tuhan putuskanlah urat-urat nadinya.” Walau tidak ada doa- doa mengancam macam itu dari warga, harapan-harapan yang terkumpul menunjukkan kalau mereka tidak (begitu saja) menerima perubahan yang akan terjadi pada tempat tinggal mereka. Ada penolakan-penolakan di sana, walau beberapa bisa jadi samar dan lirih.
Warga yang membagikan harapan-harapannya dengan Fajar juga direkam dalam seri foto potret keluarga berlatar rumah masing-masing. Seri foto ini memungkinkan kita untuk mengamati kondisi masing-masing rumah dan mengenal wajah orang- orang yang tinggal di mepet njeron beteng lor wetan itu. Fajar memanggungkan tiap keluarga bersama dengan perabot-perabot mereka dalam rumah berukuran 4×5 meter. Perkakas rumah tangga mereka disusunnya jadi menyerupai benteng yang membatasi mereka sekaligus mempertegas kesan sempit bagi rumah mereka.
Warga yang membagikan harapan-harapannya dengan Fajar juga direkam dalam seri foto potret keluarga berlatar rumah masing-masing. Seri foto ini memungkinkan kita untuk mengamati kondisi masing-masing rumah dan mengenal wajah orang- orang yang tinggal di mepet njeron beteng lor wetan itu. Fajar memanggungkan tiap keluarga bersama dengan perabot-perabot mereka dalam rumah berukuran 4×5 meter. Perkakas rumah tangga mereka disusunnya jadi menyerupai benteng yang membatasi mereka sekaligus mempertegas kesan sempit bagi rumah mereka.

/3/
Ini bukan kali pertama Fajar menggunakan pendekatan yang bermain-main dalam tataran harapan dan imajinasi atas masa depan. Proyek Better Call Shaman untuk Village Video Festival 2018, misalnya, juga hadir dengan metode yang serupa. Saya pernah bertanya kenapa dia lebih suka bermain-main dalam tataran imajinasi ketimbang advokasi ketika mengulik persoalan komunitas-komunitas tersebut. Fajar mengaku kalau pilihan itu diambil karena dia ingin membagikan masalah yang dihadapi warga yang ditemuinya tapi sekaligus mengerti kemampuannya. Dia tahu kalau pendekatan “pendampingan” macam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tidak sesuai dengan kapasitasnya.
Fajar juga bilang kalau pendekatannya selalu dia sesuaikan dengan kultur masyarakat tempatnya berproses. Better Call Shaman hadir karena Fajar memperhatikan kalau warga masih sangat terhubung dengan kekuatan supranatural untuk melancarkan bisnis mereka. Di proyek itu Fajar lalu ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh agen-agen kekuatan supranatural itu untuk mengurangi dampak industri bagi Jatiwangi. Metode kekaryaan Fajar yang mencari tahu kecenderungan warga setempat lalu merepresentasikan sekaligus mengamplikasinya juga terbaca dalam proyek Dihadapan Harapan ini. Mengumpulkan harapan-harapan warga dalam buku doa sejalan dengan identiknya doa dengan orang-orang yang pasrah. Pada saat yang sama, pendekatan ini memberi ruang bagi Fajar (juga mungkin bagi warga) untuk memaknai lagi apa-yang-disebut sebagai “kepasrahan” dan bagaimana berhadapan dengannya. Metode Fajar memang condong ke mewartakan, berbeda dengan pendekatan “fasilitasi” layaknya LSM yang semangatnya lebih ke mengadvokasi perubahan dalam masyarakat.

Namun, menuliskan ini, saya jadi berpikir kalau pertanyaan yang pernah saya lontarkan ke Fajar itu kurang tepat. Sebab ia mengandaikan dua pendekatan tersebut sebagai sesuatu yang bertolak belakang alih-alih bisa saling melengkapi. Dalam proyek ini, contohnya, bukankah di titik tertentu, Fajar, dengan merepresentasikan temuan-temuannya, memberikan data yang bisa jadi berharga untuk kerja-kerja pendampingan LSM dan aktivisme? Rekaman Fajar ini juga berarti karena mengajak kita melihat hubungan antara perubahan kota dan aspirasi warga. Lebih-lebih sebab proses relokasi warga dari kawasan ini terkesan berjalan dengan kalem. Apa yang Fajar tampilkan setidaknya membuat kita tahu riak-riak kecil di balik apa yang terlihat tenang itu.