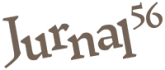Ketika Sejarah Dituturkan Melalui Sekumpulan Barbie
— Amos, penulis/peneliti Lingkar Studi Sejarah (LSS) Arungkala.

Boneka Barbie yang biasanya dipakaikan gaun, kemeja, dan sepatu gaul itu berubah. Boneka Barbie yang cantik dan ganteng, anggun dan gagah, berganti jadi sosok-sosok yang sering ditemui di sekitar rumah. Boneka Barbie itu berubah wujud jadi tukang bakso bawa HT, ibu-ibu pengajian yang berkerudung, ibu-ibu berkonde Dharma Wanita, remaja dengan jeans gaul, atau mahasiswa dengan almamaternya.
Dalam karya Tennessa Querida Waksman di pameran “Mengingat 25 Tahun Reformasi”, Barbie berubah wujud jadi subjek pencerita dan penutur sejarah. Tetapi berbeda dengan patung gagah Diponegoro atau Jenderal Sudirman, Barbie menuturkan sejarah sehari-hari orang biasa di era Orde Baru. Barbie dengan atribut pakaian sehari-hari dalam ruang keseharian adalah jalan yang dipilih Tennessa Querida Waksman untuk menuturkan sejarah.
Karya ini adalah tawaran untuk melihat sejarah secara utuh. Selama ini buku-buku sejarah menjebak perbincangan soal masa lalu pada peran tokoh, elit politik, lembaga negara, atau agensi formal yang layak diangkat dan dikenang. Sementara, mereka yang berperan pada ruang keseharian dianggap bukan penggerak sejarah. Tukang bakso, preman, waria, ibu-ibu PKK dianggap hilang sama sekali dalam gerak sejarah.

Sejarah Orde Baru seakan hanya milik Soeharto, Benny Moerdani, Ali Moertopo, dan elit politik lainnya. Penggerak sejarah seakan hanya Mafia Berkeley, PDI, PPP, Golkar, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau perusahaan-perusahaan multinasional yang membangun pabrik baru. Apa yang dianggap layak tertulis dalam buku sejarah adalah institusi formal, tokoh elit, dan megaproyek ‘pembangunan’ ekonomi.
Pembicaraan tentang sejarah selalu berputar tentang orang besar, peristiwa besar, dan lembaga-lembaga besar. Sejarah akhirnya terjebak pada narasi besar soal kekuasaan, dampaknya ada mereka yang dianggap tak punya sejarah (people without history), wajah mereka tak hadir pada buku sejarah, mereka tak penting dikenang dan didengar kisahnya.
Dinamika keseharian kemudian menjadi hal yang terlalu sepele untuk dilihat sebagai bagian dari gerak sejarah. Peristiwa seperti pidato Soeharto 1998 atau Sidang Umum MPR 1999 adalah kejadian yang layak disebut penggerak sejarah. Suatu masyarakat dianggap bisa berubah karena peristiwa besar dengan peran orang-orang besar. Sehingga menuturkan sejarah soal dinamika keseharian dianggap proyek remeh dan sia-sia.

Sejarah yang berfokus pada narasi besar itu selalu abai pada realitas historis yang utuh. Dinamika keseharian yang dikonstruksi norma dominan Orde Baru mungkin akan selalu luput dari kajian sejarah. Untuk itu, “historiografi Barbie” bisa dilihat sebagai upaya menolak sejarah sebagai narasi besar. Memaknai masa lalu lewat tubuh Barbie adalah menuturkan hal-hal sepele yang terlempar dari tangan sejarawan dalam kertas kerjanya.
Menceritakan masa lalu tanpa beban metodologis yang kaku menjadi penting. Arsip dalam kajian konvensional dianggap sebatas lembaran teks kuno, arsip tekstual itu menjadi satu-satunya sumber mendapat data-data historis. Padahal, arsip ialah semua wahana yang menjadi “lokasi penyimpanan” memori. Sebagai “lokasi penyimpanan” yang bukan sekadar teks, arsip bisa dimaknai melampaui batasan yang ada. Metafora “tubuh sebagai arsip” dari Inge Baxmann memperlihatkan upaya memaknai arsip terlepas dari gagasan umum soal tekstualitas semata [1]. Gerak dan laku performatif tubuh dapat dipahami sebagai “lokasi penyimpanan” seluruh pengalaman historis. “Tubuh sebagai arsip” memungkinkan pemaknaan sejarah sebagai pengalaman kebertubuhan yang utuh, baik secara sensorik, emosional, dan kognitif.
Jika kembali pada karya Tennessa Querida Waksman berjudul New Order Style Phenomenon, kerudung nyai, jeans, tattoo, wig seorang transpuan, konde ala Dharma Wanita, dan berbagai atribut pada tubuh Barbie bisa dilihat sebagai ‘arsip’. Sebab laku performatif tubuh berkelindan dengan atribut yang melekat padanya. Bahkan, kita bisa langsung menghubungkan atribut tubuh Barbie itu pada atribut tubuh manusia yang ingin direpresentasikan. ‘Arsip’ dalam atribut-atribut Barbie membawa kita pada memori kebendaan dan beban makna dalam tubuh yang memakainya.

Laku sang tubuh digerakkan oleh norma hegemonik di desa-desa, dapur, ruang tamu, hingga bangku di sekolah. Atribut menjadi ‘arsip’ soal laku performatif manusia yang kesehariannya wajib mematuhi peran-peran berdasarkan skenario mutlak: menjadi ibu rumah tangga, menjadi manusia Indonesia yang ekspresi gendernya tak ‘menyimpang’, menjadi pemuda yang tampilannya tak berandalan, atau menjadi intel yang diperintah menyamar jadi tukang bakso.
Orde Baru perlu dilihat sebagai siklus kuasa dibanding sekadar rezim politik. Sebagai siklus kuasa ia merasuk pada semua lini kehidupan, bahkan sampai yang paling sehari-hari. Kuasa Orde Baru yang mencengkram keseluruhan hidup itu beroperasi lewat pemantauan para intel berkedok tukang bakso, doktrinasi ‘Ibuisme’ dalam riungan PKK tingkat RT, dan segenap aparatus keseharian lainnya. Endapan makna pada kerudung, wig, handy talky, konde, hingga atribut-atribut Barbie lainnya membawa ingatan kita pada kuasa yang mengekang hidup sehari-hari.
Orde Baru telah lalu, tapi warisan, struktur kuasa, dan hegemoni darinya masih mengakar. Sejarah sering dipandang secara linier, ada linieritas waktu yang memisahkan apa yang ‘kini’ dan yang ‘lalu’. Seakan membicarakan sejarah adalah bicara tentang hal usang yang selesai di masa lalu. Meski kita sudah ada dalam masa kini, ternyata masih ada yang tertinggal dari masa lalu, ia tak pernah benar-benar selesai.
Mengisahkan tinggalan-tinggalan Orde Baru itu bisa diupayakan kesenian. Tennessa Querida Waksman dengan sekumpulan Barbie-nya menyuarakan kepatuhan subjek pada politik keseharian, ketika perbincangan sejarah yang klise menganggapnya terlalu sepele untuk dibahas. Dalam hegemoni Orde Baru yang merasuk ke desa, rumah, ruang tamu, kamar tidur, dan ruang-ruang privat, “historiografi Barbie” berhasil menuturkan politik keseharian dan realitas utuh lewat tubuh-tubuh boneka.

[1] Inge Baxmann dalam The Body as Archive. On the Difficult Relationship Between Movement and History (2007)