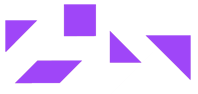This is That, This is Not That and This is only That
Esai ini adalah tulisan pengantar proyek pameran (Proyek Penutupan Pameran Wimo Ambala Bayang) This Is Not That, di Ruang MES 56, 29 Juli 2013. Ditulis oleh Brigitta Isabella.
This is That, This is Not That and This is only That
1. Distingsi
Seniman
Artists. All charlatans. Praise their disinterestedness. (Gustave Flaubert)
Ruang Galeri
Ruang galeri bukanlah ruang yang netral. Ruang galeri bukanlah ruang yang bebas konteks. Ruang galeri adalah ruang yang dikonstruksi oleh sejarah, ideologi dan kekuasaan.
Pencahayaan Artifisial
Pencahayaan artifisial memfokuskan pandangan kita pada karya seni. Memberi efek dramatis dan sakral. Memutusnya dari waktu dan menjadikannya seolah abadi. Dilarang menyentuh karya seni!
Karya Seni
Karya seni yang diletakkan di dalam ruang galeri mengalami pergeseran makna. Konten karya mendapatkan konteksnya di dalam ruang galeri, dan konteksnya menjadi konten karya itu sendiri.
2. Membongkar Pameran
Proyek pameran tunggal This Is Not That oleh Wimo Ambala Bayang bermula dari kebosanan. Dalam pusaran produksi kebudayaan yang begitu cepat, makna “membaca” tereduksi menjadi sekedar “mengonsumsi”, sedangkan kebosanan adalah ketidakmampuan menciptakan teks untuk memberi respon balik terhadap hamparan tanda yang diproduksi dengan masif di luar sana. Meski demikian, barangkali, ketidakmampuan menciptakan makna, ternyata bisa menjadi makna itu sendiri.

Memasuki ruang pamer Ruang MES 56, kita akan melihat kotak-kotak kayu dengan tulisan yang memberi informasi seperti judul karya, alamat dan nama seniman. Terbaca pula beberapa instruksi perlakuan yang umum pada karya seni, misalnya “Jangan Dibanting” atau “Hati-hati”. Oleh Wimo, kotak-kotak kayu ini “dipanggungkan”[1] dan diberi pencahayaan ala pameran pada umumnya sehingga secara bentuk kita mungkin teringat pada karya lukis Erianto dalam seri Dikembalikan (2011) di mana ia melukis citra kemasan kardus dengan teknik foto realisme di atas kanvas. Dapat pula kita membandingkannya dengan karya Wiyoga Muhardanto As Soon As Possible (2010) di booth Platform3, Art Stage Singapura yang menciptakan replika kotak kardus, pipa penyimpan lukisan dan meja, kursi sampai tas Hermes yang semuanya berbahan resin sehingga booth itu terlihat seperti ruangan yang belum ditata.[2] Proyek Wimo sebetulnya punya pertanyaan dasar yang sama tentang arti “benda seni” seperti kedua seniman yang baru saja saya sebut. Namun, alih-alih mereplika benda dan menransformasinya dengan material lain untuk menjadikannya “karya seni”, Wimo justru tengah mereplika peristiwa pameran itu sendiri.
Menarik untuk diketahui bahwa di dalam kotak-kotak kayu itu terdapat “benda seni”, sisa-sisa dari pameran kolektif MES 56 yang terbengkalai sejak dua tahun yang lalu. Kotak kayu yang dibiarkan tertutup menghalangi akses kita untuk melihat apa yang sebetulnya ada di dalamnya. Wimo juga tidak mengadakan pembukaan melainkan penutupan proyek pameran. Selama 5 minggu, sejak ia “memanggungkan” kotak-kotak kayu dengan preferensi yang ia anggap sebagai sebuah peristiwa pameran, Wimo tidak memberi informasi / teks apapun soal pameran ini. Pengunjung yang kebetulan datang ke MES 56 untuk sekedar nongkrong atau datang ke acara diskusi publik yang diadakan di lantai dua bangunan tersebut[3], menurut pengamatannya, kebanyakan sekedar sambil lalu melewati “benda-benda seni” ini tanpa sadar bahwa mereka sebenarnya sedang melihat sebuah proyek seni. Seperti seolah-olah menyindir pameran-pameran di galeri privat-komersial (biasanya berbasis rumah di Jakarta) yang “hanya dibuka dan dianggap penting” pada hari pembukaan pameran untuk melayani para kolektor, proyek ini justru sebaliknya, baru “ditahbiskan” sebagai sebuah peristiwa pameran ketika ditutup dengan perangkat standar pameran – poster publikasi, penerbitan brosur yang berisi tulisan saya sebagai pengantar dan pidato Agung Kurniawan sebagai penutup pameran. Logika yang serba dibalik ini bisa dimaknai sebagai otokritik Wimo terhadap kegerahannya menjadi aktor dalam rutinitas exhibition making; membuat karya seni – memamerkannya (sembari berharap karyanya terjual).
3. Peristiwa Pameran Sebagai Medium
Persoalan pembedaan seni dan bukan seni adalah persoalan yang sudah cukup tua di jagad seni rupa. Kita dapat menunjuk karya Marcel Duchamp, The Fountain (1917) yang berusia hampir satu abad, di mana karya ini dengan gamblang mempertanyakan secara radikal apa arti benda seni. Atau tidak perlu jauh-jauh, bukankah Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB) pada tahun 1975 juga sudah memanifestasikan gagasan menolak konsepsi seni modern dengan memamerkan benda sehari-hari di ruang galeri?
Meski demikian, proyek Wimo memperluas lagi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila Duchamp atau GSRB menghadirkan benda ready made untuk mendobrak kemungkinan medium dalam karya seni, maka Wimo menjadikan peristiwa pameran itu sendiri sebagai mediumnya. Beberapa pertanyaan dasarnya adalah: apakah yang disebut karya seni dapat mengada tanpa peristiwa pameran? Apakah aksi “memanggungkan” dan memamerkan (memajang karya seni untuk menghasilkan efek visual tertentu) dapat disebut sebagai seni? Siapa yang turut ambil peran dalam menciptakan nilai benda-benda itu sebagai “seni”?
Peristiwa pameran sebagai medium juga bukanlah hal yang baru dalam sejarah seni global. Closed Gallery (1969) adalah contoh yang menarik, di mana sang seniman, Robert Barry menutup galeri selama durasi pamerannya. Ia juga mengedarkan 4000 undangan yang bertuliskan “During The Exhibition The Gallery Will Be Closed” beserta waktu dan tiga institusi yang terlibat dalam proyek ini di Amsterdam, Turin dan Los Angeles. Ada banyak sekali orang yang kemudian menelpon untuk mengonfirmasi atau bahkan datang ke tempat pameran, dan harus menghadapi kenyataan bahwa galeri yang ditutup adalah karya Robert Barry.
Kemunculan seni konseptual tahun 60-70an dalam sejarah seni rupa menandai perkembangan masyarakat post-industrial atau masyarakat “informasi”, di mana parameter penilaian karya seni bergeser dari soal visual menjadi soal informasi. Menurut Camiel Van Winkel, seniman konseptual adalah broker informasi, di mana manual labour tidak lagi dilihat sebagai yang paling penting melainkan nilai informasi dari konsep yang digagas sang seniman.[4] Sementara itu, menarik pula bahwa Claire Bishop dalam Artificial Hells (2012) mencatat sejak tahun 90-an terma “pameran” untuk menyebut suatu peristiwa seni telah bergeser menjadi “proyek”. Terma “proyek” mewakili kecenderungan karya-karya yang berbasis proses dan bersifat partisipatif, menggeser praktik penciptaan yang berbasis objek dengan otoritas tunggal seniman sebagai sang kreator jenius.
Meski demikian, karakter seni kontemporer yang muncul di tahun 90-an ternyata mewarisi konsekuensi-konsekuensi yang diwariskan oleh seni konseptual 60-70an. Apabila seni konseptual melakukan pendobrakan medium dengan aksi-aksi paling absurd yang tidak terbayangkan sebelumnya untuk menggerus komersialisasi dalam seni, maka bukankah kini justru ia telah sampai pada perkembangannya yang mapan dan mereproduksi rezim yang sebelumnya ditantang?
Ketika Wimo memanggungkan kotak-kotak kayu yang pun bukan berisi karyanya sendiri, apa yang menjadikannya seni? Ketika seorang seniman, katakanlah Duchamp yang membubuhkan namanya pada sebuah benda sesederhana urinal, atau Robert Barry yang menyatakan bahwa galeri yang ditutup adalah karyanya, apakah mereka adalah produser tunggal dari penciptaan hal yang kemudian dapat disebut seni ini? Tindakan ini tidak akan memiliki makna tanpa adanya suatu ekologi yang memuliakan nilai yang tidak hanya diukur dari harga produksinya, atau yang disebut Bourdieu (1992) sebagai nilai simbolik. Nilai simbolik ini berhutang pada keajaiban logika yang diciptakan dan diamini oleh suatu ekologi sosial dalam tradisi pengapresiasian seni sehingga kita kemudian merayakan dan dibuat percaya bahwa suatu benda asing yang diletakkan seniman di ruang galeri adalah seni. Penelitian sosiologis Bourdieu dalam The Rules Of Art (1992) menyatakan bahwa, “The producer of the value of the work of art is not the artist but the field of production as a universe of belief which produces the value of the work of art as a fetish by producing the belief in the creative power of the artist” (hlm 29). Kepercayaan kolektif kita akan nilai simbolik suatu benda diwarisi oleh suatu rezim pengetahuan yang turun temurun kita reproduksi tanpa sadar, menciptakan suatu sistem yang tak lebih dari sekedar suatu permainan ilusi.
Saya kira, yang menarik dari proyek pameran This Is Not That adalah karena ia menciptakan suatu ilusi untuk membicarakan ilusi dan menantang kepercayaan kita untuk melangkahi batas rasionalitas umum. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa menerima dan percaya bahwa apa yang dilakukan Wimo ini layak disebut sebagai seni atau sekedar sebuah kesia-siaan yang tak berujung?
Brigitta Isabella
25 Juli 2013
[1] Saya menggunakan kata memanggungkan untuk mengacu pada istilah “staging” ketimbang “displaying” (menata), karena berangkat dari modus atau praktik staged photography yang dilakukan Wimo beberapa tahun terakhir (hati-hati membedakan “stage photography” dan “staged photography”).
[2] Seri lukisan Erianto adalah pengakuan ironis atas pengembalian karya-karya seni “lokal” yang tidak diterima di pusat-pusat seni internasional karena kurang pantas dipamerkan di arena global. Meski secara bentuk cukup menarik, bagi saya gagasan di balik karya ini justru bernada orientalis yang kurang percaya diri. Sementara, instalasi Wiyoga dengan modus replika 1:1 yang biasa ia lakukan untuk mengaburkan objek seni dan benda sehari-hari sangat menarik karena konteksnya yang dibuat sebagai site-specific installation di acara art fair.
[3] Pada tanggal 12 Juli 2013 diadakan presentasi publik oleh seniman residensi The Secret Agents di Ruang MES 56 dan ada cukup banyak orang yang hadir pada acara tersebut.
[4] Camiel Van Winkel, During The Exhibition the Gallery Will Be Closed, Valiz, Amsterdam, 2012, hlm 13.