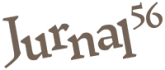Sebelum (re)Reformasi: Catatan Residensi Youth of Today 2023 [Bagian Pertama]
— Savitri Sastrawan, kurator pameran “Mengingat 25 Tahun Reformasi”.

Refleksi Posisi Perempuan dalam “Mengingat 25 Tahun Reformasi”
Saat bersinggah pada sebuah kuliah umum oleh Saskia Wieringa yang diadakan RUAS (Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan) di UGM akhir bulan Januari 2023, ada yang menggelitik dari pemikirannya. Ia menyatakan sudah saatnya ada feminisme nusantara dan tidak berkiprah ke apa yang berkembang disebut Barat. Ini tidak lepas dari riset besarnya yang menelusuri perjuangan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) sebagai bagian kedudukan perempuan yang sudah penuh pergerakan selama 20 tahun sejak kemerdekaan Indonesia, berubah menjadi bagian dari Ibu-Ibu PKK yang sopan dan nurut saat Orde Baru.
Saskia menjelaskan bahwa Gerwani telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia sama siapnya sebagai pasukan pembela negara bersama para pria. Ini memberikan kesempatan untuk para perempuan memiliki citra ‘militan’ dan ‘berani’ daripada sebagai perempuan yang diam saja sebagai istri maupun ibu di rumah – yang mereka sangat bantah [1]. Bahkan, Gerwani memberi atensi kepada keberadaan ibu rumah tangga yang luput dari cakupan PKI (Partai Komunis Indonesia). Sedangkan PKK sangat menuruti permintaan pemerintah pusat (Jakarta) terhadap posisi perempuan di seluruh Indonesia. Mereka tidak ada perlawanan dan malah berharap mendapatkan sesuatu yang baik dari organisasi tersebut [2].
Menurut Alia Swastika, pembubaran Gerwani membuat perempuan tidak saja “dijinakkan secara politis”, tetapi termasuk pula “kesadaran atas tubuh, seksualitas dan individualitas dibatasi”. Ini lalu menyebabkan perbincangan tentang hal-hal itu termasuk dalam kesenian menjadi ‘tabu’ [3]. Ini juga terlihat dalam tulisan Wieringa yang membahas perbedaan Orde Lama dengan Orde Baru adalah adanya tiga “sumbu utama”: gender, nasionalisme dan politik seksual [4]. Serta merta, Presiden Soeharto menjadi super-patriarch atau ‘bapak’ dari keluarga pembangunan di era Orde Baru [5]. Dengan ia menjadi bapak, istrinya menjadi citra Ibu yang sangat dijunjung dan patut dicontoh oleh perempuan Indonesia. Ke-Jawa-sentris-an pemerintah pusat menjadi yang harus diikuti oleh perempuan Indonesia yang sebenarnya beragam.

Dijabarkan juga oleh Alia bahwa Soeharto pernah menyatakan “dasar pemikiran” yang “memunculkan konsep baru ibu rumah tangga” yang notabene memang bermaksud “meletakkan posisi ibu sebagai kodrat biologis” serta “menyangkal hak-hak personal mereka sebagai individu”. Dan saya lihat ini menjadi pegangan perempuan Indonesia yang ‘sempurna’ di Orde Baru,
“Organisasi perempuan itu memberikan jalan kepada perempuan untuk menjalani posisi dan peran yang benar, yaitu menjadi ibu rumah tangga dan secara berkelanjutan menjadi motor bagi pembangunan… Kita tidak boleh melupakan kodrat mereka sebagai pihak yang harus terus menyediakan keberlanjutan hidup yang sehat, baik, dan membahagiakan” [6]
Perlu diketahui bahwa kata perempuan dan wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang berbeda. Perempuan dijabarkan sebagai manusia yang mempunyai puki dan menjalankan kodrat biologisnya, sedangkan Wanita adalah istri atau bini. Sedangkan jika dicari dari akar bahasa Jawa-nya, wanita berarti diinginkan – seakan perempuan adalah objek laki-laki [7]. Bisa jadi Gerwani yang menggunakan kata Wanita daripada Perempuan berangkat menjadi kata yang juga dilawan terhadap posisi perempuan yang direpresi dari sebelumnya.
Penjabaran sejarah kedudukan perempuan di Indonesia dari zaman pra-kemerdekaan, kemerdekaan, Orde Baru, Reformasi sampai sekarang, tidaklah bisa diceritakan dengan singkat. Tetapi yang bisa ditangkap dari sumber-sumber ini bahwa ada kecenderungan menghentikan pergerakan progresif perempuan di rezim Orde Baru dengan memanipulasi nama serta wajah Gerwani saat kejadian G30S karena kedekatannya dengan partai terbesar yang ingin dimatikan yaitu PKI (Partai Komunis Indonesia). Lalu, dalam sebuah artikel yang membuat review terhadap buku Wieringa berjudul Sexual Politics in Indonesia, Sawyer Martin French menyatakan:
“Menurut Wieringa, Suharto justru membutuhkan citra kekejian Gerwani untuk dikambingkitamkan demi memperkukuh rezimnya. Dalam masyarakat “pasca-Orba”, bukankah saatnya mitos-mitos semacam itu dibongkar?” [8]
Di kesenian saya rasa ada jejak-jejak di mana saat Pasca-Orba atau Pasca Reformasi pembongkaran dengan pelurusan sejarah yang dinyatakan dimanipulasi pada tahun 1965 – tertuang dalam bentuk karya maupun tulisan. Setidaknya, sejak Reformasi tahun 1998, karya maupun tulisan tersebut mencerminkan lagi sebuah pergerakan perempuan yang menyangkal citra perempuan Indonesia yang sempurna – menjadi Ibu – yang sempat terasa samar bahkan hilang di era Orde Baru.
Kesadaran atas “ideologi politik” serta “pertarungan kekuasaan” adalah salah dua yang menjadi pemikiran-pemikiran yang berkembang, tidak terkecuali dengan kacamata feminisme [9]. Dalam tulisan Carla Bianpoen, Farah Wardani, dan Wulan Dirgantoro berjudul Women in Indonesian Modern Art: Chronologies and Testimonies, disebutkan saat Reformasi terjadi, gender tetap merupakan “non-issue” di dalam politik Indonesia sampai Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki kemungkinan untuk menang menjadi pemimpin di tahun 1999,
“Seketika gender menjadi topik hangat dan argumen menentang dipimpin seorang perempuan berdasarkan keyakinan agama, menggebu” [10]
Studi dan analisa gender, aktivisme perempuan, kembali menghentakkan kaki lagi, ditambah yang telah menjadi ‘tabu’ di Orde Baru, menjadi bagian dari kekaryaan perempuan Indonesia lagi, yakni keterlibatan tubuh. Namun, feminisme dilihat terlalu radikal serta tidak sesuai dengan norma Indonesia. Padahal ke-karyaan-nya menyentuh ideologi yang ingin posisi melawan patriarki maupun represi terhadap perempuan [11].

Adanya penyangkalan perempuan perupa menyatakan dirinya feminis seharusnya tidak menjadi masalah. Karena di saat karyanya bisa dibaca dengan perspektif feminisme, artinya ada pesan yang memang ingin disampaikan yang sesuai dengan ideologi itu. Dengan itu di sana tetap ada perjuangan yang bisa direfleksikan banyak orang, terutama untuk perempuan Indonesia di zaman itu sampai sekarang.
Seperti yang saya sebut di atas, Reformasi telah memberikan kesempatan banyak orang untuk mengungkapkan pendapatnya lebih bebas. Kebebasan itu dan dengan perkembangannya teknologi, memberikan kesempatan untuk para perupa memakai berbagai media serta bergerak di berbagai disiplin, daripada fokus pada pencapaian estetika saja. Setelah tahun 2000, banyak inisiasi perupa, kolektif, ruang-ruang alternatif, kolaborasi dengan berbagai disiplin termasuk bekerja di industri kreatif, terjadi di dalam skena seni visual [12]. Maka kecenderungan media-media baru daripada seni rupa yang formal muncul ke permukaan. Ditambah para perempuan perupa tidak lagi terbelenggu dalam posisinya di ruang privat maupun publik serta posisi-posisi politisnya,
“..perkembangan seni saat ini telah menjadi berbagai dinamika multidimensional” [13]
Dengan demikian, pemikiran maupun distribusi pengetahuan semakin kaya dengan karya-karya perempuan perupa masuk di dalam sejarah seni rupa Indonesia. Walaupun ada kecenderungan figur ibu dan perbincangan kodrat muncul di permukaan karya perempuan perupa, maknanya sangat bisa dilihat dari berbagai perspektif di saat sekarang. Setidaknya kita bisa saling mengisi narasi atau sejarah yang hilang sejak Reformasi terjadi, apalagi dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan itu bisa lebih cepat terjadi. Begitu juga dengan pandangan posisi perempuan di segala ranah ruang, belum lagi kemungkinan-kemungkinan pandangan posisi perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan inisiasi seperti proyek “Kata Untuk Perempuan” oleh perupa Ika Vantiani, gerakan sosial perempuan secara daring maupun langsung yang mendukung sesama perempuan, dan juga perspektif Pertiwi yang masih didengungkan, saya rasa dengan ini pandangan feminisme maupun perempuan nusantara bisa terus dikembangkan.
Dan yang paling esensial, seorang “ibu rumah tangga” adalah seorang perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang tidak terkekang hanya pada kodrat biologisnya maupun pekerjaan rumah. Ia sangat boleh menelusuri pengetahuan baru bahkan potensi-potensinya untuk keberlangsungan hidupnya secara fisik dan mental.
[1] Saskia E. Wieringa (1993) Two Indonesian women’s organizations: Gerwani and the PKK, Bulletin of Concerned Asian Scholars 25 (2), hal.19.
[2] Ibid, hal. 20.
[3] Alia Swastika (2019) Membaca Praktik Negosiasi Seniman Perempuan dan Politik Gender, Yogyakarta, Indonesia, hal. 38.
[4] Saskia E. Wieringa (2003). The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism. Journal of Women’s History 15(1), hal. 71.
[5] Ibid, hal. 72.
[6] Swastika, Membaca Praktik Negosiasi Seniman Perempuan dan Politik Gender, hal. 33-34.
[7] Ibid, hal. 32.
[8] Sayer Martin French, Gerwani, Kepanikan Seksual, dan Kemunculan Orde Baru, The Suryakanta, 30 September 2022, diakses 29 Januari 2023, tautan: thesuryakanta.com
[9] Swastika, Membaca Praktik Negosiasi Seniman Perempuan dan Politik Gender, hal. 24.
[10] Carla Bianpoen, Heather Waugh, eds. (2007) Indonesian Women Artists: The Curtain Opens. Jakarta: Yayasan Senirupa Indonesia, hal. 31
[11] Ibid, hal. 31.
[12] Ibid, hal. 32.
[13] Ibid.