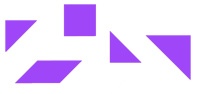Faraway So Close
Tulisan ini merupakan materi teks diskusi pameran “Faraway So Close” yang diselenggarakan di Galeri Semarang pada tanggal 27 April 2013. Ditulis oleh Agung Nugroho Widhi.
Faraway So Close [1. Judul tulisan serta judul pameran ini diambil dari sebuah film karya sineas Jerman, Wim Wenders (1993).]
Membaca judul di atas, mungkin kita akan beranggapan bahwa ini adalah sebuah permainan kata-kata belaka atau suatu pemikiran yang dualistis. Judul tulisan yang sekaligus merupakan judul pameran kolektif MES 56 ini, berusaha “berbicara tentang Semarang”, sebuah kota yang
terletak di sebelah utara Jogja, dengan jarak tempuh kurang lebih empat jam.
Secara umum, karya-karya yang ditampilkan dalam pameran ini “membicarakan Semarang” dalam dua artian, yaitu Semarang sebagai entitas bentang fisik (physical landscape) dan sebagai bentang mental (mental landscape) yang mengacu pada “gagasan atau narasi besar tentang Semarang.” Secara tematik, karya-karya yang ditampilkan MES 56 dalam Faraway So Close bisa dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu karya-karya yang membicarakan memori, jarak, dan ketertampakan (visibility). Tiga kelompok karya tersebut semuanya dibingkai serta terangkum dalam tiga buah kutipan[2. Ketiga kutipan yang dimaksud bisa dilihat dalam katalog pameran, dan merupakan kutipan beberapa dialog dari film yang menjadi judul pameran ini.] yang juga disajikan di ruang pameran.
Tulisan ini berupaya untuk membaca ulang gagasan pameran dan karya-karya yang dipresentasikan, baik karya-karya personal para anggota MES 56 maupun karya kolektif.
I.
Gagasan dari proyek pameran ini bisa dibayangkan sebagai suatu laku perjalanan. Berjalan-jalan keluar rumah, untuk sementara waktu pergi meninggalkan tempat asal menuju ke sebuah tempat baru dengan jarak tempuh yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Dengan bekal pengalaman, pengetahuan, dan segala agenda yang akan dijalankan di tempat baru yang didatangi itu, kita hanyalah seorang tamu.
Berada di suatu tempat yang baru, tentu kita akan bertemu dengan orang-orang baru. Para tuan rumah. Orang-orang lokal, yang meskipun menggunakan bahasa serta mengonsumsi makanan yang relatif sama, namun memiliki cara pandang yang mungkin sangat jauh berbeda dengan kita dalam melihat lingkungan dan rumah yang di tinggalinya. Di tempat baru itu pula, kita akan berhadapan dengan perspektif seorang tuan rumah dalam melihat lingkungan serta “rumah” yang mereka tinggali.
Pada fase ini, jarak tidak lagi berada dalam tataran fisik, namun telah bergeser menjadi sebuah interaksi yang lebih kompleks. Menjadi antara kita dengan mereka. Kita yang suatu waktu adalah mereka, dan mereka yang suatu waktu sekaligus kita. Antara melihat dan dilihat, membaca dan (untuk) dibaca, mengamati dan teramati.
II.
Bagian ini akan menggali dua konsep atau tematik dalam beberapa karya yang dipamerkan, tentang jarak dan ketertampakan (visibility).
Saya mencoba untuk melangkah mundur ke belakang dan berusaha untuk memposisikan diri sepenuhnya sebagai seorang “penonton”, untuk dapat lebih memberikan gambaran tentang proyek pameran ini. Menginjakkan kaki di suatu tempat yang baru dan asing, mungkin kita akan dihadapkan dengan berbagai fakta, fenomena, ataupun lanskap yang belum tentu sepenuhnya baru. Dalam situasi maupun kondisi tertentu, seniman juga tak ubahnya seorang turis, yang ingin terus merekam dan mengingat segala sesuatu yang tampak dipermukaan (façade),seolah-olah segalanya menarik dan terlihat baru.
Gagasan tentang “ketertampakan” (visibility), bisa kita amati melalui dua karya kolektif MES 56 yang ditampilkan di lantai bawah Galeri Semarang. Di karya kolektif berjudul Untitled, yang berupa foto di lembar fiber dan instalasi suara itu, kita melihat dan mendengar imaji juga suara-suara yang selama ini sering kita temui dan dengar setiap harinya di Semarang. Dalam instalasi tersebut, terpampang belasan snapshot yang menggambarkan kota Semarang seperti yang pernah, atau bahkan mungkin sering kita lihat. Kawasan Kota Lama yang terendam banjir, interior serta pilar-pilar penyangga Pasar Johar, tumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, dan lain sebagainya.
Pada ruangan lain di lantai bawah, tersaji empat kanal video yang diproyeksikan ke atas empat lembar multiplex bekas. Semuanya menggambarkan Semarang dalam penampakan yang sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan dalam karya sebelumnya. “Semarang yang bukan Semarang.” “Semarang yang bisa dimana saja”. Momen-momen acak, fragmen-fragmen antah berantah yang tak bertuan.
III.
Kesadaran akan sebuah jarak haruslah disertai dengan pengamatan lebih lanjut, untuk bergerak menjauhi berbagai perasaan dari pengalaman melihat yang sifatnya seketika. Hal ini memang bukan perkara mudah, dan tidak semua seniman mampu melakukannya. Seniman bukan lagi hanya seorang turis yang seolah-olah berjalan tanpa tujuan, namun ia juga seorang pengamat, yang gerak-geriknya akan selalu diamati oleh orang lain; si tuan rumah.
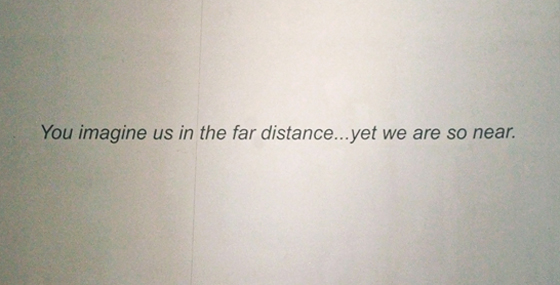
Menilik kembali konsep tentang visibility maupun jarak, saya mencoba untuk melihatnya melalui beberapa karya yang dipamerkan di lantai atas Galeri Semarang. Kita akan lihat bagaimana karya-karya ini membicarakan Semarang dalam dua artian sebagaimana tersebut diatas; sebagai physical landscape dan mental landscape. Saya akan mengambil contoh karya instalasi interaktif kolaborasi Rangga Purbaya dan Wok The Rock, Jarak Pandang: Candi Baru, Semarang. Karya ini berupa rekaman wawancara dengan dua orang Semarang, disertai foto lanskap suatu kawasan bernama Candi Baru[3. Kawasan ini dibangun pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1916, dan khusus diperuntukkan sebagai kawasan tempat tinggal orang-orang Belanda dan bangsa Eropa. Pada masa itu, Oei Tiong Ham, si raja gula sekaligus Majoor der Chinezen di Semarang adalah satu-satunya orang non-Eropa yang mendapatkan hak istimewa untuk tinggal di kawasan Candi Baru.] yang dipresentasikan melalui sebuah layar sentuh (tablet), serta juga diproyeksikan ke dinding ruang pameran. Dengan ukuran gambar yang sangat besar dan terekam dengan detil yang amat tajam (ultra high resolution), kita bisa memilih tiap bagian, lalu melihat secara rinci elemen-elemen yang tampak dalam foto itu. Rumah demi rumah yang dibangun di atas tanah berbukit, warna dan potongan setiap jemuran pakaian di depan pintu rumah, maupun aktivitas tiga orang manusia yang berada disana. “Sejauh apa kita mengetahui dan seberapa dekat kita mampu melihat ini semua?”
Karya Yudha Kusuma Putra, Flowers of an Old City membawa perihal jarak ke dalam suatu tataran yang lebih kompleks. Melalui karyanya, Yudha mencoba untuk menelaah kembali jarak serta fungsi seniman, seni, maupun institusi seni (peran sebuah galeri seni) di dalam kehidupan sosial kita. Apa yang ditampilkan Yudha dalam foto-fotonya adalah “orang-orang yang sepertinya dekat”; potret-potret sembilan wanita dan seorang anak kecil yang tinggal tepat di seberang Galeri Semarang. Dalam karya Yudha, jarak bukan hanya dalam pengertian fisik, namun juga merupakan sebuah metafor; “jarak antara kita dengan orang lain, jarak antara seni, seniman dengan lingkungan sosialnya”. Kota Semarang maupun kawasan Kota Lama hanyalah sebagai latar yang tidak terlalu penting, karena gagasan yang dibicarakan dalam karya ini bisa ditemui dimana saja. Semarang hanyalah sebatas pijakan untuk membicarakan sebuah narasi besar yang melampaui kota itu.
Titik pijakan yang serupa juga bisa dilihat melalui salah satu seri karya Akiq AW, Anatomy of Common Sense. Dalam karyanya, Akiq merujuk pada sebuah institusi yang berada di Semarang, yaitu Museum Rekor Indonesia (MURI). Dengan menggunakan data dan foto-foto dari MURI, karya Akiq berusaha untuk menelisik apa yang selama ini kita pahami sebagai “akal sehat” (common sense). Rekor-rekor yang tercatat di MURI memberikan pada kita gambaran tentang bagaimana manusia Indonesia melihat diri disendiri, masyarakat dan dunia luar. Penonton bisa membaca dan melihat bagaimana “akal sehat” itu di bangun dan ditelusupkan pada kesadaran kita, tentang bagaimana “berbagai peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang tidak masuk akal menjadi masuk akal, yang biasa menjadi tidak biasa (uncommon)”.
IV.
Dalam berbagai percakapan serta diskusi dengan anak-anak Mes sepanjang proses pameran ini, saya beberapa kali mendengar cerita bahwa seringkali mereka dihadapkan pada suatu pandangan yang terlalu nostalgis tentang Semarang dari orang-orang yang mereka temui selama berada disana. Hanya segelintir orang saja yang (mampu) bercerita panjang lebar tentang wajah Semarang hari ini, pun demikian halnya dengan tulisan Tubagus Svarajati dalam katalog pameran juga menceritakan pengalamannya pada sebuah peristiwa di Semarang bulan Mei 1998.
Andri William dan Edwin Roseno mengolah memori dan sekelumit sejarah tentang kota Semarang dalam karya-karyanya. Andri dan Edwin Roseno (biasa dipanggil Dolly) menggunakan pendekatan serupa, yang meningatkan saya pada karya kolektif MES 56, Unfolded City (2005)[4. Unfolded City membenturkan persepsi kita tentang konsepsi waktu, antara Jogja di saat tertentu (masa lalu) dengan Jogja di saat yang lain (masa kini). Apa yang kita sebut sebagai “dulu” dan “sekarang”, atau sesuatu yang kita anggap representasi dari “masa lalu” dan “masa kini” ditumpuk ke dalam satu layer dan dihadirkan pada saat yang sama. Karya ini merupakan karya kolektif MES 56 yang pernah dipresentasikan di Biennale Jogja 2005 “Disini & Kini”.] dan teks di salah satu foto dari seri Oma, karya Yudhi Soerjoatmodjo.[5. Oma adalah salah satu diantara tiga karya fotografi yang dipamerkan di Jakarta Biennale IX (Desember 1993 – Januari 1994), dikuratori oleh Jim Supangkat. Beberapa tahun kemudian, karya ini kembali dipamerkan dalam pameran Orientasi/ Orientatie di Galeri Nasional, Jakarta (1995) dan Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden (1996). Oma terakhir kali ditampilkan dalam Serendipity: Photography, Video, Experimental Film and Multimedia Installation from Asia (The Japan Foundation Forum, Tokyo, 2000).] Berikut saya kutip teks tersebut di bawah:
Sometimes I think photography fails me. How does one photograph the past? The language of words is equipped to deal with time: there are words that can fill the hole of our past, words to build a future. But one can only photograph in the physical present. Right now. Even though “right now” becomes a past once we photographed it.
Dalam seri Scratched Memory, Dolly menumpuk serta menghadirkan dua layer yang berbeda di setiap foto-fotonya. Lapisan terluar dari karya-karya Dolly adalah sketsa beberapa situs atau bangunan di Semarang pada masa silam yang dieksekusi di atas selembar akrilik dengan teknik laser engraving, sedangkan lapisan keduanya adalah foto-foto bangunan atau lanskap situs-situs itu hari ini. Semuanya telah berubah serta beralih fungsi. Empat bangunan yang dulu merupakan gedung pertemuan, pusat kebudayaan dan pendidikan, sekarang telah berubah wujud menjadi pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya.
“Di Semarang itu mas, kalo gak pelakunya (anak muda) yang pergi, ya tempatnya yang pergi”[6. Pernyataan dari Bentar, salah satu subyek yang ditampilkan Andri William dalam fotonya.]
Mengambil titik tolak serupa dengan Dolly, Andri William dengan karyanya Should I Stay or Should I Go memilih sebuah tempat bernama Ventura Mas (orang Semarang biasa menyebutnya kolam renang eks stadion). Bangunan tua peninggalan Belanda yang selama belasan tahun pernah dijadikan area nongkrong muda-mudi kota Semarang, tempat bermain papan luncur (sekaligus skate park pertama di Pulau Jawa) dan sepeda BMX. Sama halnya dengan empat bangunan yang ditampilkan Dolly dalam karya-karyanya, latar yang dipilih Andri ini sekarang juga telah berganti wajah.
Dalam dua fotonya, Andri menghadirkan orang-orang yang dulu biasa menghabiskan waktunya disana; para skater dan anak-anak BMX. Benar memang, kita tidak bisa memotret masa lalu, kita hanya bisa menghadirkan atau membacanya melalui selembar foto. “Ingatan saya” tentang sebuah film dibawah, mungkin dapat menjelaskan hal ini dengan lebih baik.
Dua hari berselang setelah kejadian mengenaskan yang menewaskan Robert F. Kennedy (Bobby Kennedy) di Hotel The Ambassador, New York, Paul Fusco, seorang fotografer dari agensi foto Magnum, berada di dalam kereta yang membawa peti jenazah senator sekaligus calon presiden Amerika Serikat termuda itu ke Arlington National Cemetery, Virginia.
Sepanjang perjalanan dari New York ke Arlington, Fusco memotret orang-orang yang berada di luar dari dalam gerbong kereta. Ratusan bahkan ribuan wajah yang menangis terisak, berdiri memberi hormat ala militer, atau membentangkan berbagai spanduk dan pamflet dengan tulisan-tulisan yang menyiratkan penghormatan dan kecintaan mereka pada Bobby.
Hampir empat puluh tahun kemudian, seorang sutradara film, Jennifer Stoddart, menelusuri wajah-wajah yang terekam oleh kamera Fusco. Dibantu oleh beberapa orang kru dan narasumber, ia akhirnya bertemu dengan mereka, yang empat puluhan tahun lalu menunggu dan melihat sebuah gerbong berisi peti jenazah melintas.[7. Penelusuran yang dilakukan Jennifer Stoddart atas foto-foto Paul Fusco diproduksi dalam sebuah film berjudul One Thousand Pictures: RFK’s Last Journey (2010).]
Dalam dua seri yang mereka kerjakan, Dolly maupun Andri tidak hanya menelusuri serta membahas masa lalu yang serba nostalgis dan romantis, atau membicarakan masa lalu demi masa lalu itu sendiri (old days for the sake of the old days), namun menjadikan masa lalu sebagai pintu masuk untuk membicarakan Semarang hari ini. “Right now”. Seperti penelusuran Stoddart atas foto-foto Fusco, karya-karya mereka bukanlah sekadar catatan atau rekaman masa lampau, melainkan penciptaan kembali ingatan.
V.
Sepertinya sungguh tidaklah mungkin untuk berandai-andai atau bernostalgia tentang Semarang seperti halnya orang-orang Semarang yang ditemui oleh anak-anak Mes, maupun tulisan Tubagus Svarajati dalam katalog pameran.
Saya membayangkan ini semua seperti ketika melihat karya atau proyek residensi yang dilakukan oleh seniman-seniman yang pernah tinggal dan bekerja untuk sementara waktu di Jogja. Dalam situasi seperti itu, pikiran yang merujuk pada suatu pemahaman “locally correct” atau “culturally correct” memang tidak bisa dihindari lagi. Namun terlepas dari segala macam persoalan salah-benar, tepat-tidak tepat, siapa melihat siapa, tentu akan memunculkan sebuah “cara pandang baru” sebagai semacam tawaran dari cara pandang sebelumnya, yang dianggap terlalu mapan dan mungkin dirasa mulai membosankan.
Poin paling penting dalam karya-karya yang ditampilkan MES 56 dalam proyek pameran ini adalah, seberapa dekat karya-karya itu dapat membaca dan melihat berbagai fenomena di sebuah tempat yang “relatif jauh dan asing”. Jarak memang akan selalu ada, bahkan sudah seharusnya tetap ada, dan saya sepenuhnya percaya pada apa yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf nun jauh di sana ribuan tahun lalu, bahwa jarak akan membuat seorang manusia menjadi lebih bijak.
Semoga.
Agung Nugroho Widhi
Ruang MES 56